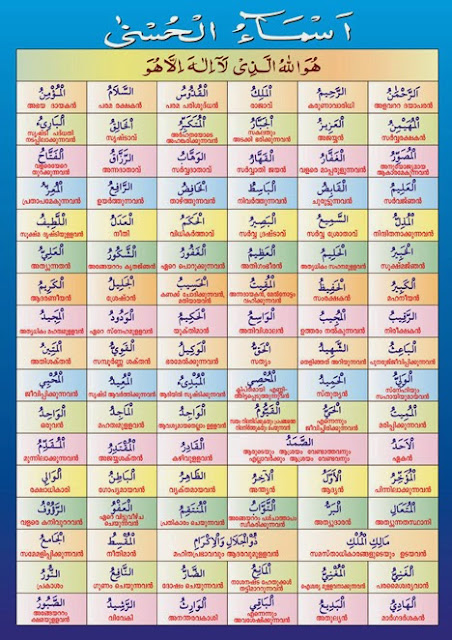MAKHRIJAL HURUF
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Pendidikan
agama
Dosen Pengampu:
Suhendri, S.Pd.I.M.Pd
KATA PENGANTAR
Segala puji serta syukur penulis
haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang atas limpahan rahmat, karunia, serta
hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah TAJUWID
dengan tema “Defenisi Makharijul Huruf.
Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. karena berkat beliaulah
sehingga pada saat ini dapat merasakan indahnya Islam dan nikmatnya Iman.
Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada bapak Suhendri, S.Pd.I, M.Pd Selaku dosen pengajar yang telah memberikan
arahan yang begitu berarti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan makalah ini. Juga kepada teman-teman yang telah membantu secara
langsung atau tidak langsung dari pengumpulan bahan hingga penyelesaian.
Tak ada gading yang tak retak,
penulisan sadari dalam penulisan ini tak akan pernah lepas dari kesalahan dan
kekurangan, maka untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan koreksi dari
bapak dosen ataupun dari teman-teman agar penulis dapat dapat lebih baik pada
masa akan datang.
Bangkinang, oktober 2017
Penulis
DAFTAR PUSTAKA
Latar
Belakang………………………………………………………………………
Daftar
Isi…………………………………………………………………………….
BAB
I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang…………………………………………………………………..
B.
Rumusan Masalah……………………………………………………………….
C.
Tujuan Penulisan………………………………………………………………...
BAB
II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Makhrijal Huruf……………………………………………………...
B.
Tempat keluar huruf ( makhraj )…………………………………………………
C. Tanda
Baca……………………………………………………………………….
D.
Tanda Wakaf ( berhenti )………………………………………………………...
E.
Hukum Bacaan…………………………………………………………………...
BAB
III PENUTUP
A.
Kesimpulan………………………………………………………………………
B.
Saran……………………………………………………………………………..
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Sebelum kita masuk pada pokok
pembahsan kita, lebih biak kita ketahui bahwa tajuwid adalah suatu bahan yang
sangat berguna bagi kita ketika membaca al-quran, apalagi yang berkenaan dengan
bagaimana cara menyebut huruf yang tepat atau dengan benar. Jadi untuk
itu perlu kita pelajari dan kita ketahui bersama tempa-tempat keluarnya huruf
dan sifat-sifatnya. Yang selaanjutnya dipakai sebagai bahan latihan secara
individu dengan terus menerus, agar dapat tepat sesuai dengan kaidah kaidah
pengucapan huruf yang benar.
Ilmu tajwid adalah ilmu yang
mengajarkan cara bagaimana seharusnya membunyikan atau membaca
ghuruf huruf hijaiyah ang baik tajwid diadan sempurna .baik ketika
sendirian maupun bertemu dengan huruf lain. Tajwid adalah
membetulkan dan membaguskan bunyi bacaan al qur’an menurut aturan aturan
hukumnya yang tertentu. Aturan-aturan itu diantara lain yaitu mengenai:
1. Hukum bacaan (cara-cara membaca)
2. Makharijul huruf (tempat-tempat keluar
huruf)
3. Shifatil huruf (sifat-sifat huruf )
4. Ahkamul huruf (hukum yang tertentu
bagi tiap tiap huruf )
5. Mad (ukuran bagi panjang atau
pendeknya sesuatu bacaan )
6. Ahkamul waqauf (hukum hukum bagi penentuan
berhenti atau tersnya suatu bacaan)
Dari berbagai aturan-aturan yang telah
disebutkan diatas maka pada kesempatan kali ini pemakala akan membahas mengenai
Makharijul huruf (tempat-tempat keluar huruf).
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa
pengertian makhrijal huruf ?
2.
Dimana
saja tempat keluar huruf ?
3.
Apa
saja tanda baca ?
4.
Apa
saja tanda wakaf ?
5.
Bagaimana
dengan hokum bacaan ?
C.
Tujuan Penulisan
1. Supaya kita menjadi lebih baik
ketika membaca al-quran
2. Supaya membaca al-quran dengan
benar dan tepat
3. Supaya kita membaca al-quran lebih
bagus
4. Supaya mengetahui makhrijal huruf
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian makhrijal huruf
Makhorijul huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan
huruf al-Qur’an. Pengertian makhraj dari segi bahasa adalah tempat keluar.
Sedangkan dari segi istilah makhraj diartikan tempat keluarnya huruf.
Mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah adalah sangat penting karena
hal ini menjadi dasar dalam melafadzkan huruf hijaiyyah secara benar.
B.
Tempat keluar huruf ( makhraj )
Yang dimaksud dengan makhraj adalah tempat
asal keluarnya sebuah huruf dari huruf-huruf hujaiyah. Dimana dalam membaca al-Qur’an makhorijul
Qur’an harus diketahui dan benar-benar dipahami dalam rangka untuk menciptakan
bacaan al-Qur’an yang baik dan benar.
makhrijul huruf adalah menyebutkan atau membunyikan huruf huruf
yang ada dalam al qur’an .Yang mana banyak semuanya
berjumlah 19 buah, terbagi kedalam 5 Mawadhi’.Maka yang dikatakan dengan
Mawadhi ialah tempat letaknya makharaj-makharaj .
1. Maudhi’ Jauf (مو ضع ا جو ف )
Artinya tempat makhraj yang terletak di rongga
mulut .jauf artinya rongga.Mengandung satu makhraj, yang dinamakan juga dengan
Makhraj-Jauf.Makhraj al-jauf (rongga mulut ) adalah tempat keluarnya huruf
mad artinya huruf-huruf panjang. yang banyaknya adalah 3.
a. Alif( ا) mati yang sebelumnya berbaris fatah
b. Waw(
و )mati yang sebelumnya berbaris di depan
Contoh :
قو موا كو
نوا قا
لو تصو مو
ن
c. Yaa
mati (ي) sebelumnya berbaris dibawah (kasrah)
Contoh
:
اَ لَّذ
ِيْ
2. Maudhi’ Halq
(مو ضع ا لحلق )
Artinya tempat makhraj yang terletak di
rekungan. halq artinya rekungan. Huruf hurufnya yaitu :
خ غ ح ع ه ء
Maudi’halq mengandung tiga makhraj, yang
dinamakan dengan:
a. Aqshal-Halq artinya
pangkal rengkungan
Makhraj aqshal halq (pangkal rekungan ) adalah
tepat keluarnya
2 macam huruf yaitu Hamzah dan Ha besar
Misalnya :
ا نهم ا كلها
هدا
b. Washthal-Halq artinya
pertengahan rengkungan adalah tempat keluarnya dua macam huruf pula yaitu
“Ain dan Ha
Misalnya :
عنهم محيطا محشر
عَلَقٍ
عَلَّمَ
يَعْلَم
c. Adnal-Halq artinya ujung
Rekungan. Adalah tempat keluarnya dua macam huruf juga yaitu ghain dan
kha
Misalnya:
غير هم من غل ا خبا
ر خَلَقَ
3. Maudhi’ lisan (
مو ضع اللسا ن )
Artinya tempat makhraj yang terletak di lidah
lisan artinya lidah. Mengandung 10 MAKHRAJ, yang dinamakan dengan:
a. Pangkal lidah dengan
langit-langit adalah tempat keluarnya satu huruf yaitu Qaf
(ق)
Misal:
قا تل مقربو
ن متقين
ا قر
خلق
b. Dimuka pangal lidah
dengan langit-langit sedikit adalah tempat
keluarnya satu huruf yaitu Kaf (ك)
Misal :
ر
بك
الا كر م
ايا ك
لكم ا
كبر
c.
Ditengah lidah dengan lngit-langit adalah keluar dari pada tiga huruf
yaitu: Jim, Syim, dan Yaa
Misal :
ج : جها
ر جاهد
ش : من الشيطان شقا وة
ي :
ا يا
ي
يايه
d. Tepi lidah
dengan geraham kiri atau kanan adalah keluar dari padanya satu huruf
yaitu: Dhad (ض)
Misal :
ضرا ر
e. Kepala lidah adalah
keluar daripadanya satu huruf yaitu Lam (.ل.)
Misal:
لاا له الاالله
f. Dimuka kepala lidah sedikit .Keluar
daripadanya satu huruf yaitu Nun (ن)
Misal :
ا نا
منهم
g. Didekat makhraj (Nun)
adalah keluar daripadanya satu huruf yaitu: RA (ر.)
Misal:
ر جا
ل
h. Ujung lidah
dengan urat gigi yang diatas adalah keluar daripada tiga huruf Ta, Dal dan Tha
Misal :
ت : تكو ن متقو ن
ر شد ا
:
د
ط: طا لوت طو ب
i. Ujung lidah
dengan papan rat gigi yang diatas adalah keluar daripadanya tiga huruf Zai,
Sin, dan Shad
Contoh
:
ز بو را ر زا :
ز
با
سم سو ا
ه اسحق : س
صر اط صو را
: ص
j. Ujung lidah
dengan ujung gigi yang diatas adalah keluar dari tiga huruf yaitu: Tsa, Dzal
dan Zha
Contoh :
ثل
ثة ثقيلة
ذ
ليل ذ را ع
4. Maudhi
’Syafatain ( مو ضع الشفتين )
Artinya tempat makhraj ag terletak di dua
bibir syafatain artinya dua bibir. Mengandung 4 (empat) makhraj yang
dinamakan dengan:
a. Dua
perut lidah sebelah keluar
Keluar dari padanya satu huruf, yaitu : Mim
( م)
contohnya:
مما ملكت من مثله
عَلَّمَ بِا لْقَلَمْ
مَا لَمْ يَعْلَمْ
b. Dua
perut bibir sebelah kedalam,
keluar dari padanya satu (1) huruf yaitu Ba (ب)
contohnya :
رَ
بِّكَ
با
ب ا بو ا ب
c. Perut
bibir yang dibawah dengan ujung gigi yang diatas .keluar padanya satu huruf yaitu fa (ف)
contohnya :
فَاا فْعَلُوْا كَا ِفرُ وْ
ن
فتر ضى
فاا فعلوا كفا
ية
d. Antara
dua bibir . keluar padanya satu huruf yaitu Waw (و) , yang tidak huruf mad
Contohnya :
وَوَا عَدْ نَا وَ رَ
بُّكَ
و و فيت
5. Maudhi’ Khaisyum ( مو ضع ا لخيشو م )
makhraj
yang terletak dipangkal hidung khaisum artinya pangkal hidung. Keluar dari padanya segala bunyi dengung (ghunnah)
Misalnya pada waktu huruf nun dan
mim ketika bertasydid atau ketika ikhfa .Al Khaisyum ( pangkal
hidung ) yang sebenarnya bukanlah tempat keluar huruf ,hanya karena
dengung itu ada hubungannnya dengan huruf .maka ia disebut juga makhraj .
hars diketahui bahwa yang sesungguhnya semua huruf tidak boleh
dikeluarkan melalui hidung .
Contohnya :
اَ مَّا لَمَّا اَ نَّا
مِنْ بَيْنَهُمْ
C.
Tanda Baca
Harakat digunakan
untuk mempermudah cara melapazkan huruf dalam tiap ayat Al Quran bagi seseorang
yang baru belajar dan memahami atau mengenal tanda baca dalam membaca
dan melapazkan alquran.
Macam-macam tanda baca lainnya atau
macam harakat, diantaranya adalah :
1.
Fathah
Fathah (فتحة)
adalah harakat yang berbentuk seperti garis horizontal kecil atau tanda petik (
ٰ ) yang
berada di atas suatu huruf Arab yang melambangkan fonem (a). Secara harfiah,
fathah itu sendiri berarti membuka, layaknya membuka mulut saat mengucapkan
fonem (a). Ketika suatu huruf diberi harakat fathah, maka huruf tersebut akan
berbunyi (-a), contonya huruf lam (ل ) diberi harakat fathah
menjadi “la” (لَ ). Cara melafazkannya
ujung lidah menempel pada dinding mulut.
2. . Alif Khanjariah
Tanda
huruf ALif Khanjariah sama halnya dengan Fathah, yang juga ditulis layaknya
garis vertikal seperti huruf alif kecil ( ٰ
) yang diletakkan diatas atau disamping kiri suatu huruf Arab,
yang disebut dengan mad fathah atau alif khanjariah yang melambangkan fonem (a)
yang dibaca agak panjang. Sebuah huruf berharakat fathah jika diikuti oleh Alif
(ا)
juga melambangkan fonem (-a) yang dibaca panjang. Contohnya pada kata “laa” (لاَ)
dibaca dua harakat.
3. Kasrah
Kasrah (كسرة)
adalah harakat yang membentuk layaknya garis horizontal kecil ( ِ ) tanda baca yang
diletakkan di bawah suatu huruf arab, harakat kasrah melambangkan fonem (i).
Secara harfiah, kasrah bermakna melanggar. Ketika suatu huruf diberi harakat
kasrah, maka huruf tersebut akan berbunyi (-i), contonya huruf lam (ل)
diberi harakat kasrah menjadi (li) (لِ).
Sebuah
huruf yang berharakat kasrah jika bertemu dengan huruf “ya” (ي )
maka akan melambangkan fonem (-i) yang dibaca panjang. Contohnya pada kata ” lii ”
( لي)
dibaca 2 harakat.
4. Dammah
Dammah (ضمة)
adalah harakat yang berbentuk layaknya huruf ” waw “( wau) (و) kecil yang diletakkan di
atas suatu huruf arab ( ُ ),
harakat dammah melambangkan fonem (u). Ketika suatu huruf diberi harakat
dammah, maka huruf tersebut akan berbunyi (-u), contonya huruf ” lam ”
(ل)
diberi harakat dammah menjadi (lu) (لُ).
Sebuah
huruf yang berharakat dammah jika bertemu dengan huruf
“waw” (و
) maka akan melambangkan fonem (-u) yang dibaca panjang.
Contohnya pada kata (luu) (لـُو).
5. Sukun ( hara’kat )
Sukun (سکون)
adalah harakat yang berbentuk bulat layaknya huruf “ha” (ه)
yang ditulis di atas suatu huruf Arab. Tanda bacanya bila ditulis seperti huruf
(o) kecil yang bentuknya agak sedikit pipih. Harakat sukun melambangkan fonem
konsonan atau huruf mati dari suatu huruf, misalkan pada kata “mad” (مـَدْ)
yang terdiri dari huruf mim yang berharakat sehingga menghasilkan bunyi fathah (مَ) dibaca “ma”,
dan diikuti dengan huruf “dal” (دْ) yang berharakat sukun yang menghasilkan
konsonan atau bunyi (d) sehingga dibaca menjadi “mad” (مـَدْ).
Harakat
sukun juga misa menghasilkan bunyi diftong, seperti (au) dan (ai), cotohnya
pada kata (نـَوْمُ) yang berbunyi (naum)u)) yang
berarti tidur, dan juga pada kata (لَـيْن) yang berbunyi (lain) yang
berati lain atau berbeda.
6. Tasydid
Tasydid ( تشديد)
atau yang disebut syaddah ( شدة) adalah harakat yang
bentuk hurufnya (w) yang diberi atau seperti kepala dari huruf “sin” (س)
yang diletakkan di atas huruf arab (ّ ) yang letaknya diatas suatu
huruf Arab. Harakat tasydid melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang
dituliskan dengan simbol konsonan ganda, sebagai contoh pada kata ( شـَـدَّةٌ)
yang berbunyi (syaddah) yang terdiri dari huruf syin yang berharakat fathah (ش)
yang kemudian dibaca (sya), diikuti dengan huruf “dal “yang berharakat
tasydid fathah ( دَّ) yang menghasilkan bunyi
(dda), diikuti pula dengan ta marbuta ( ةٌ) di akhir kata yang
menghasilkan bunyi (h), sehingga menjadi (syaddah).
7. Tanwin
Tanwin (bahasa
Arab: التنوين, “at tanwiin”) adalah tanda baca (diakritik)
harakat pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut
diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati.
8. Wasal
Wasal (bahasa Arab: وصلة, dibaca: washlat)
adalah tanda baca atau diakritik yang dituliskan pada huruf Arab yang biasa
dituliskan di atas huruf alif atau yang disebut juga dengan Alif wasal. Secara
ilmu tajwid, wasal berarti meneruskan tanpa mewaqafkan atau menghentikan
bacaan.
Harakat
wasal selalu berada di permulaan kata dan tidak dilafazkan apabila berada di
tengah-tengah kalimat, namun akan berbunyi layaknya huruf hamzah apabila dibaca
di awal kalimat.
Contoh
alif wasal:
i.
ٱهدنا
ٱلصرط
“ihdinas
shiraat”
Bacaan
tersebut memiliki dua alif wasal, yang pertama pada lafaz “ihdinaa” dan “as
shiraat” yang manakala kedua lafaz tersebut diwasalkan atau dirangkaikan dalam
pembacaannya maka akan dibaca “ihdinas shiraat” dengan menghilangkan pembacaan
alif wasal pada kata “as shiraat”.
Lihat
contoh berikut dibawah ini :
ii.
نستعين
ٱهدنا ٱلصرط
“nasta’iinuh
dinas shiraat”
Bacaan
di atas terdiri dari kata “nasta’iin”, “ihdinaa dan as shiraat”, dengan
mewasalkan lafaz “ihdina” dengan lafaz sebelumnya, sehingga menghasilkan lafaz
“nasta’iinuh dinaa”, dengan mewasalkan lafaz “as shiraat” dengan lafaz
sebelumnya, maka akan menghasilkan lafaz “nasta’iinuh dinas shiraat”.
Alif
wasal lebih sering dijumpai bersamaan dengan huruf lam atau yang disebut juga
dengan alif lam makrifah pada lafaz dalam bahasa Arab yang mengacu kepada kata
yang bersifat isim atau nama.
Contoh
alif wasal dalam alif lam makrifah:
iii.
ٱلصرط
“as
shiraat”
ٱلبقرة
“al
baqarah”
ٱلإنسان
“al
insaan”
iv.
9. Waqaf
Waqaf
dari sudut bahasa artinya berhenti atau menahan, manakala dari sudut istilah
tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir
perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Waqaf
dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya :
– ﺗﺂﻡّ (taamm) –
waqaf sempurna – yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang
dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan
tidak mempengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan
dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya.
– ﻛﺎﻒ (kaaf)
– waqaf memadai – yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan secara
sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, namun ayat
tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya.
– ﺣﺴﻦ (Hasan)
– waqaf baik – yaitu mewaqafkan bacaan atau ayat tanpa mempengaruhi makna atau
arti, namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya.
– ﻗﺒﻴﺢ (Qabiih)
– waqaf buruk – yaitu mewaqafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak
sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat, wakaf ini harus
dihindari karena bacaan yang diwaqafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya
dengan bacaan yang lain.
D. Tanda Wakaf ( berhenti )
Waqaf artinya berhenti di
suatu kata ketika membaca Al-Qur'an, baik di akhir ayat maupun ditengah ayat
yang disertai nafas. Sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut saktah.
Berhenti ketika melakukan tilawah Al-Qur'an
memerlukan pengetahuan yang khusus, agar tilawah terdengar bagus. Ali bin
Abu Thalib ra. menafsirkan kata-kata At-Tartil dalam surat Al Muzzammil ayat 4
dengan : أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
"Membaguskannya dan mengetahui tempat-tempat perberhentian yang
tepat."
Untuk mengetahui
tempat-tempat berhenti yang tepat diperlukan pemahaman terhadap ayat-ayat yang
dibaca, sehingga setiap pemberhentian memberi kesan arti yang sempurna. Oleh
karena itu, bagi mereka yang sudah memahami Al-Qur'an dengan baik, maka dirinya
dapat menentukan pemberhentian yang tepat walaupun tanpa terikat dengan
tanda-tanda waqaf.
1.
Tanda mim( مـ )
Tanda mim disebut juga
dengan Waqaf Lazim. yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf Lazim
disebut juga Wakaf Taamm (sempurna) karena wakaf terjadi setelah kalimat
sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya.
Contoh ; An-Naml: 36
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
" Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan
orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian
kepada-Nya-lah mereka dikembalikan".
2. Tanda Laa ( ﻻ ) bermaksud "Jangan berhenti!".
Tanda ini muncul kadang-kala
pada penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat,
maka tidak dibenarkan untuk berhenti dan jika berada di penghujung ayat,
pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak.
Contoh : An-Naml: 63
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
"(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam
keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka):
"Salaamun´alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang
telah kamu kerjakan".
3.
Tanda sad-lam-ya‘ ( ﺻﻠﮯ )
Tanda sad-lam-ya‘
merupakan singkatan dari "Al-wasl Awlaa" yang bermakna "wasal
atau meneruskan bacaan adalah lebih baik", maka dari itu meneruskan bacaan
tanpa mewaqafkannya adalah lebih baik.
Contoh:An-Naml: 17
وَإِنْ
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
"Dan jika Allah menimpakan sesuatu
kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia
sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu."
4.
Tanda jim ( ﺝ )
Tanda jim adalah Waqaf
Jaiz. Lebih baik berhenti seketika di sini walaupun diperbolehkan juga untuk
tidak berhenti.
Contoh: Al-Anfal: 13
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
"(Ketentuan) yang demikian itu adalah
karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa
menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras
siksaan-Nya."
5.
Tanda Waqaf Aula (قل )
Tanda waqaf Aula
yaitu anda waqaf yang menunjukkan lebih bagus berhenti walaupun nafas masih
kuat.
Contoh : Fussilat : 45
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ
فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ
"Dan sesungguhnya telah Kami berikan
kepada Musa Taurat lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada
keputusan yang telah terdahulu dari Rabb-mu, tentulah orang-orang kafir itu
sudah dibinasakan. Dan Sesungguhnya mereka terhadap Al Quran benar-benar dalam
keragu-raguan yang membingungkan."
6.
tanda bertitik tiga (.'. .'.~Mu'anaqah)
bertitik tiga yang disebut
sebagai Waqaf Muraqabah atau Waqaf Ta'anuq (Terikat). Waqaf ini akan muncul
sebanyak dua kali di mana-mana saja dan cara membacanya adalah harus berhenti
di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak
perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya.
Contoh Al-Baqorah: 2
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
7.
. Tanda tho ( ﻁ )
Tanda tho adalah tanda Waqaf Mutlaq yaitu boleh berhenti dan boleh terus,
tapi lebih baik berhenti. Contoh :
Å7Î=»tB ÏQöqtƒ ÉúïÏe$!$# ÇÍÈ
8. Tanda wakaf mustahab (قف)
Tanda wakaf mustahab
berhenti lebih utama, tapi terus/washol juga boleh.
9.
Tanda
Waqaf Mujawwaz (ز )
Tanda wakaf mujawwaz yaitu tanda boleh berhenti, namun meneruskan bacaan
adalah lebih utama.
10.
Tanda
sad ( ﺹ )
disebut juga dengan Waqaf Murakhkhas,
menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun diperbolehkan berhenti
saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda dan sad adalah
pada fungsinya, dalam kata lain lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf sad.
11.
Tanda
qaf ( ﻕ )
merupakan
singkatan dari "Qeela alayhil waqf" yang bermakna "telah
dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya", maka dari itu lebih baik
meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan.
12.
Tanda
sin ( س ) atau tanda Saktah ( ﺳﮑﺘﻪ )
menandakan
berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah
berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk meneruskan bacaan.
13. Tanda sad ( ﺹ
)
disebut juga dengan Waqaf
Murakhkhas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti namun
diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara
hukum tanda zha dan sad adalah pada fungsinya, dalam kata lain lebih
diperbolehkan berhenti pada waqaf sad.
E.
Hukum Bacaan
1.
Hukum Bacaan Nun Mati/ Tanwin
Nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ)
jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah,hukum bacaannya ada 5 macam, yaitu:
a)
Izhar
(إظهار)
Izhar artinya jelas atau terang. Apabila ada nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ)bertemu
dengan salah satu huruf halqi (ا ح خ ع غ ه ), maka dibacanya jelas/terang.
b)
Idgham
(إدغام)
Idgham Bighunnah (dilebur dengan disertai dengung)
Yaitu memasukkan/meleburkan huruf nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) kedalam
huruf sesudahnya dengan disertai (ber)dengung, jika bertemu dengan salah satu
huruf yang empat, yaitu: ن م و يIdgham
Bilaghunnah (dilebur tanpa dengung)
Yaitu memasukkan/meleburkan huruf nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ / نْ) kedalam
huruf sesudahnya tanpa disertai dengung, jika bertemu dengan huruf lam atau ra
(ر، ل)
c)
Iqlab
(إقلاب)
Iqlab artinya menukar atau
mengganti. Apabila ada nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ /
نْ) bertemu dengan huruf ba (ب), maka
cara membacanya dengan menyuarakan /merubah bunyi نْ menjadi
suara mim (مْ), dengan merapatkan dua bibir serta mendengung.
d)
Ikhfa
(إخفاء)
Ikhfa artinya menyamarkan atau tidak
jelas. Apabila ada nun mati atau tanwin (ـًـٍـٌ /نْ) bertemu dengan salah satu huruf ikhfa
yang 15 (ت ث ج د ذ س ش ص ض ط ظ ف ق ك ), maka dibacanya samar-samar, antara
jelas dan tidak (antara izhar dan idgham) dengan mendengung.
2.
Hukum Bacaan Mim Mati
Mim mati (مْ) bila bertemu dengan huruf hijaiyyah,
hukumnya ada tiga, yaitu:ikhfa syafawi, idgham mim, dan izhar syafawi.
a.
Ikhfa
Syafawi (إخفاء سفوى)
Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan ba
(ب),
maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan.
b.
Idgham
Mimi ( إدغام ميمى)
Apabila mim mati (مْ) bertemu dengan mim (مْ), maka cara membacanya adalah seperti
menyuarakan mim rangkap atau ditasyidkan dan wajib dibaca dengung.Idgham mimi
disebut juga idgham mislain atau mutamasilain.
c.
Izhar
Syafawi (إظهار سفوى)
Apabila mim mati (مْ) bertemu
dengan salah satu huruf hijaiyyah selain huruf mim (مْ) dan ba (ب), maka
cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup
3. Pengertian Qalqalah
Menurut bahasa qalqalah artinya gerak, sedangkan menurut istilah
qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul bila ia mati atau dimatikan, atau
suara membalik dengan bunyi rangkap. Adapun huruf qalqalah terdiri atas lima
huruf, yaitu : ق , ط , ب , ج , د agar mudah
dihafal dirangkai menjadi قُطْبُ جَدٍ
Macam-macam Qalqalah
a. Qalqalah kubra (besar)
yaitu Huruf Qalqalah yang berbaris hidup, dimatikan karena waqaf. inilah
Qalqalah yang paling utama, cara membacanya dikeraskan qalqalahnya.
Contoh : مَا خَلَقَ . أُوْلُوا
اْلأَلْبَابِ . زَوْجٍ بَهِيْجٍ .
b. Qalqalah Sugra (kecil)
yaitu Huruf Qalqalah yang berbaris mati, tetapi tidak waqaf padanya,caranya
membacanya kurang dikeraskan Qalqalahnya.
Contoh : يَقْطَعُوْنَ
إِلاَّ إِبْلِيْسَ وَمَا أَدْرَاكَ
3.
Hukum membaca Ra
hukum bacaan Ra terbagi menjadi tiga,yaitu:
a.
Ra dibaca Tafkhim artinya tebal, apabila keadaannya sbb:
1. Ra berharkat fathahاَلرَّسُوْلَ
2. Ra berharkat dhummahرُحَمَاءِ
3. Ra diwakafkan sebelumnya huruf yang berharkat fathah atau Dhummahيَنْصُرُ- َاْلاَبْتَرُ
4. Ra sukun sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau dhummahتُرْجَعُوْنَ- يَرْحَمٌ
5. Ra sukun karena wakaf sebelumnya terdapat alif atau wau yang matiاَلْغَفُوْرُ-اَلْجَبَّارُ
6. Bila ra terletak sesudah Hamzah Washalاُرْكُضْ-
اِرْحَمْنَا
Catatan:Hamzah Washal adalah Hamzah yang apabila terletak dia
diawal dibaca, tetapi kalau ada yang mendahuluinya dia tidak dibaca
b. Ra dibaca tarqiq (tipis) apabila keadaannya sebagai berikut:
Ra
dibaca Tarkik bila:
1.Ra berharkat kasrah رِحْلَةَ الشّتَاءِ _
تَجْرِيْ
2. Ra sukun sebelumnya huruf berharkat kasrah dan sesudahnya bukanlah huruf
Ist’la’فِرْعَوْنَ – مِرْيَةٌ
3. Ra sukun sebelumnya huruf yan berharkat kasrah dan sesudahnya huruf Ist’la’
dalam kata yang terpisah. فَصْبِرْصَبْرًا
4. Ra sukun karena wakaf, sebelumnya huruf berharkat kasrah atau ya sukun.
جَمِيْعٌ مُنْتَصِرٌ – يَوْمَئِذِ لَخَبِيْرٌ
5. Ra sukun karena wakaf sebelumnya bukan huruf huruf Isti’la’dan sebelumnya
didahului oleh huruf yang berbaris kasrah.ذِيْ
الذِّكْر
Catata:huruf Isti’lak ialah melafalkan huruf dengan mengangkat
pangkal lidah kelangit-langit yang mengakibatkan hurfnya besar ق ص ض ظ ط غ خ
d.
Ra
boleh dibaca tafkhim atau tarqiq:
Ra
dibaca tarkik dan tafkhim bila:
1. Ra sukun sebelumnya berharkat kasrah dan sesudahnya huruf Isti’la’ berharkat
kasrah atau Kasratain.مِنْ عِرْضِهِ – بِحِرْص
2. Ra sukun karena wakaf, sebelumnya huruf Isti’la’ yang berbaris mati, yang
diawali dengan huruf yang berharkat kasrah.الْقِطْرِ –
مِصْرِ
5. Hukum Bacaan Maad
Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad ada
tiga yaitu : ا و ي
Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu :
1.
Mad Ashli / mad thobi’i
Mad Ashli / mad thobi’I terjadi apabila :
– huruf berbaris fathah bertemu dengan alif
– huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya mati
– huruf berbaris dhommah bertemu dengan wawu mati
Panjangnya adalah 1 alif atau dua harokat.
contoh :
2.
Mad far’i
Adapun jenis mad far’i ini terdiri dari 13 macam, yaitu :
1)
Mad Wajib Muttashil
Yaitu setiap mad thobi’i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya
adalah 5 harokat atau 2,5 alif. (harokat = ketukan/panjang setiap suara)
Contoh :
2) Mad Jaiz Munfashil
Yaitu setiap mad thobi’i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda.
Panjangnya adalah 2, 4, atau 6 harokat (1, 2, atau 3 alif).
Contoh :
3) Mad Aridh Lisukuun
Yaitu setiap mad thobi’i bertemu dengan huruf hidup dalam satu
kalimat dan dibaca waqof (berhenti).
Panjangnya adalah 2, 4, atau 6 harokat (1, 2, atau 3 alif). Apabila tidak
dibaca waqof, maka hukumnya kembali seperti mad thobi’i.
Contoh :
4) Mad Badal
Yaitu mad pengganti huruf hamzah di awal kata. Lambang mad madal
ini biasanya berupa tanda baris atau kasroh tegak .
Panjangnya adalah 2 harokat (1 alif)
Contoh :
5) Mad ‘Iwad
Yaitu
mad yang terjai apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berbaris
fathatain dan dibaca waqof.
Panjangnya 2 harokat (1 alif).
Contoh :
6) Mad Lazim Mutsaqqol Kalimi
Yaitu bila mad thobi’i bertemu dengan huruf yang bertasydid.
Panjangnya adalah 6 harokat (3 alif).
Contoh :
7) Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi
Yaitu bila mad thobi’i bertemu dengan huruf sukun atau mati.
Panjangnya adalah 6 harokat (3 alif).
Contoh :
8)
Mad Lazim Harfi Musyba’
Mad ini terjadi hanya pada awal surat dalam al-qur’an. Huruf mad ini ada
delapan, yaitu :
Panjangnya
adalah 6 harokat (3 alif)
Contoh :
9) Mad Lazim Mukhoffaf harfi
Mad ini juga terjadi hanya pada awal surat dalam al-qur’an. Huruf mad ini ada
lima, yaitu :
Panjangnya
adalah 2 harokat.
Contoh :
10)
Mad Layyin
Mad ini terjadi
bila :
huruf berbaris fathah bertemu wawu mati atau ya mati, kemudian terdapat huruf
lain yg juga mempunyai baris.
Mad ini terjadi di akhir kalimat kalimat yang dibaca waqof (berhenti).
Panjang mad ini adalah 2 – 6 harokat ( 1 – 3 alif).
Contoh :
11) Mad Shilah
Mad ini terjadi pada huruh “ha” di akhir kata yang merupakan dhomir
muzdakkar mufrod lilghoib (kata ganti orang ke-3 laki-laki).
Syarat yang harus ada dalam mad ini adalah bahwa huruf sebelum dan sesudah “ha”
dhomir harus berbaris hidup dan bukan mati/sukun.
Mad shilah terbagi 2, yaitu :
a)
Mad Shilah Qashiroh
Terjadi bila setelah “ha” dhomir
terdapat huruf selain hamzah. Dan biasanya mad ini dilambangkan dengan baris
fathah tegak, kasroh tegak, atau dhommah terbalik pada huruf “ha” dhomir.
Panjangnya adalah 2 harokat (1 alif).
Contoh :
b) Mad Shilah Thowilah
Terjadi bila setelah “ha” dhomir
terdapat huruf hamzah.
Panjangnya adalah 2-5 harokat (1 – 2,5 alif).
Contoh :
12) Mad Farqu
Terjadi bila mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid dan
untuk membedakan antara kalimat istifham (pertanyaan) dengan sebuutan/berita.
Panjangnya 6 harokat.
Contoh :
13) Mad Tamkin
Terjadi bila 2 buah huruf ya bertemu dalam satu kalimat, di mana ya
pertama berbaris kasroh dan bertasydid dan ya kedua berbaris sukun/mati.
Panjangnya 2 – 6 harokat (1 – 3 alif).
Contoh :
6.
HUKUM BACAAN ALIF LAM
Dalam ilmu tajwid dikenal hukum bacaan alif lam ( ال ). Hukum bacaan
alim lam ( ال) menyatakan bahwa apabila huruf alim lam ( ال ) bertemu dengan
huruf-huruf hijaiyah, maka cara membaca huruf alif lam ( ال ) tersebut terbagi
atas dua macam, yaitu alif lam ( ال ) syamsiyah dan alif lam ( ال )
qamariyah
1.
Pengertian
hukum bacaan “Al” Syamsiyah.
“Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam mati yang bertemu dengan
salah satu huruf syamsiyah dan dibacanya lebur/idghom (bunyi “al’ tidak
dibaca).
Huruf-huruf tersebut adalah ت ث د ذ ر ز
س ش ص ض ط ظ ل ن
Ciri-ciri
hukum bacaan “Al” Syamsiyah:
a. Dibacanya dileburkan/idghom
b. Ada tanda tasydid/syiddah ( ) di atas huruf yang terletak setelah alif lam
mati => الـــّ
Contoh:
وَالشَّمْسِ يَوْمُ الدِّيْنِ
وَالضُّحَى
2.
Pengertian
hukum bacaan “Al” Qamariyah
“Al” Qamariyah adalah “Al” atau alif I lam mati yang bertemu dengan
salah satu huruf qamariyah dan dibacanya jelas/izhar.
Huruf-huruf tersebut adalah : ا ب ج ح خ ع
غ ف ق ك م و ه
Ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah:
a. Dibacanya jelas/izhar
b. Ada tanda sukun ( ْ ) di atas
huruf alif lam mati => الْ
Contoh:
اَلْهَادِى وَالْحَمْدُ
بِاْلإِيْمَانِ
BAB III
PENUTUP
A.
Kesumpulan
Ilmu tajwid
adalah ilmu yang mengajarkan cara bagaimana seharusnya membunyikan
atau membaca ghuruf huruf hijaiyah ang baik tajwid diadan sempurna
.baik ketika sendirian maupun bertemu dengan huruf lain. Makhorijul huruf
adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf al-Qur’an.
Harakat digunakan
untuk mempermudah cara melapazkan huruf dalam tiap ayat Al Quran bagi seseorang
yang baru belajar dan memahami atau mengenal tanda baca dalam membaca
dan melapazkan alquran.
artinya berhenti di suatu
kata ketika membaca Al-Qur'an, baik di akhir ayat maupun ditengah ayat yang
disertai nafas. Sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut saktah.
B.
Saran
Sebagai hamba allah swt, kita harus patuh dan
taat terhadap perintahnya, memohon lindungan dan rahmat darinya. Kita diberi
pedoman oleh allah untuk hidup dengan baik di dunia yaitunya alquran dan
hadist. Dalam membaca alquran kita perlu mengetahui bagaimana cara membaca dan
mengamalkan alquran dengan baik, makanya kami mmberikan sedikit
gambarannya/pelajaran yaitu tentang tempat keluar huruf, tanda baca,tanda wakaf
dan hokum tajwid, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan tolong
dipelajari katna ini sangat penting bagi kita semua, terutama umat muslim yang
berpegang teguh pada alquran.
DAFTAR PUSTAKA
Drs.H. Bambang Imam Supeno SH. MSc,2004. Pelajaran Tajwid, penerbit Insan Amanah,Bandung.
Abdullah, 1987. Pelajaran Tajwid. Penerbit
“Apollo Lestari”, Surabaya.
A.Munir dkk,1994. Ilmu Tajwid Dan Seni Baca Al Qur’an .
Penerbit Rineka Cipta,Surabaya.
Ismail.Tekan , 2006. Tajwid Al Qur’anul Karim , Penerbit PT Pustaka Al Husna Baru,
Jakarta.
Ali
ustman al-qirtosi, 2011. dasar-dasar
ilmu tajwid waqof-ibtida’,
Pamekasan biro taman pendidikan alquran pp. Miftahul Ulum Bettet.
Drs. H. A. Nawawi Ali,2002. Pedoman membaca
alquran. Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta
dhezun-notes.blogspot.com
http://amses.blogspot.co.id/2012/02/hukum-hukum-bacaan-ilmu-tajwid.html
Drs.H. Bambang Imam Supeno SH. MSc,2004. Pelajaran Tajwid, penerbit Insan Amanah,Bandung h. 10
A.Munir dkk,1994. Ilmu Tajwid Dan Seni Baca Al Qur’an . Penerbit Rineka Cipta,Surabaya. hal 84.
Ismail.Tekan , 2006. Tajwid Al Qur’anul Karim , Penerbit PT Pustaka Al Husna Baru, Jakarta, h .21
Ali ustman al-qirtosi, 2011. dasar-dasar ilmu tajwid
waqof-ibtida’, Pamekasan biro taman pendidikan alquran pp. Miftahul Ulum Bettet, h. 41
Ustaz Ismail Tekan ,2006. Tajwid Al Qur’anul Karim.
Penerbit :PT Pustaka Al Husna Baru,
Jakarta, h. 77